Internalisasi Budaya Palang Pintu Betawi sebagai Media Pembelajaran Pantun Siswa di Sekolah Dasar
Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang beragam tersebar di seluruh penjuru negeri, karena banyaknya kearifan lokal yang ada di bumi Indonesia negara ini seringkali mendapatkan keunikan tersendiri di setiap daerahnya. Ibu kota Indonesia misalnya, Jakarta, tempat ini dulunya memiliki mayoritas suku betawi yang memiliki banyak kearifan lokal yang sudah sering kita dengar, seperti ondel-ondel, namun dibalik besar dan uniknya ondel-ondel, ternyata ada loh kearifan lokal asal suku betawi ini yang tidak kalah unik dan keren, Palang Pintu namanya.
Konon pada mulanya palang pintu dikenal luas oleh masyarakat betawi melalui sebuah cerita terkenal yaitu si pitung, Pitung memiliki kisah unik dimana ia adalah anak betawi asli yang ingin menikahi seorang gadis betawi yang bernama Aisyah, anak dari seorang pesohor bernama Murthadho yang merupakan seorang jawara kemayoran, untuk dapat menikahi Aisyah, Pitung harus berhasil melewati terlebih dahulu sang jawara, yaitu sang ayah dengan cara pantun dan silat. Si Pitung berhasil mengalahkan Murtadho dan berhasil menikahi Aisyah yang menjadi pujaan hatinya. Palang Pintu sendiri adalah tradisi pernikahan adat Betawi dari kata “Palang” yang berarti penghalang agar sesuatu atau seseorang tidak dapat melewatinya. Jadi Palang Pintu bermakna agar pihak pria berusaha untuk meyakinkan pihak keluarga wanita agar mendapatkan restu untuk menikahi anak perempuan mereka (Gustiana, 2023).
Palang Pintu sendiri sudah dilakukan menjadi tradisi pernikahan di adat batak sejak 1980-an bersamaan dengan adanya tradisi ondel ondel, lebih tepatnya tradisi ini berasal dari Betawi tengah dan Betawi kota, sedangkan untuk Betawi pinggiran sendiri juga memiliki tradisi Palang Pintu namun penyebutannya berbeda, yaitu Rebut Dandang. Di balik suasana meriah yang terdapat di Palang Pintu, ada pelajaran yang sederhana namun sangat kuat, bagaimana berkata dengan santun, bagaimana menyampaikan maksud dengan halus, dan bagaimana menutup pertemuan dengan doa yang baik. Palang pintu bukan sekadar tontonan, ia adalah etika yang dipentaskan, lengkap dengan urutan salam, pantun berbalas, hingga prosesi lanjutan sebelum akad berlangsung (Melinda & Paramita, 2018).
Gambar 1. Palang Pintu
(Sumber: https://www.nowjakarta.co.id/buku-betawi-palang-pintu-a-unique-betawi-proposal-tradition/)
Dalam tradisi ini, dua kelompok berjumpa di depan rumah mempelai perempuan. Para jawara mewakili masing-masing pihak, mereka beradu pantun sebagai jembatan komunikasi, lalu melanjutkan ke segmen lain yang bersifat simbolik. Meski ada unsur “adu” di sana, inti palang pintu bukan soal menang kalah, melainkan negosiasi kehormatan dan saling hormat, tuan rumah memuliakan tamu, tamu memuliakan tuan rumah. Setelah palang benar-benar “terbuka”, barulah rombongan dipersilakan masuk sebagai alur rapi yang menegaskan bahwa kata dan budi berjalan beriringan (Wibowo & Ayundasari, 2021).
Di sekolah dasar, pelajaran ini terasa dekat. Pantun memberi struktur yang jelas, empat baris per bait, dua baris sampiran dan dua baris isi, dengan rima a-b-a-b, sementara palang pintu memberi jiwa sopan santun, apresiasi, penutup yang baik (Kemendikbudristek, 2021). Keduanya bisa dibawa ke kelas tanpa membuat suasana berat. Saya membayangkan pembelajaran Bahasa Indonesia yang tidak menggurui, melainkan mengajak siswa merasa dulu, baru menalar, pemantik singkat lewat foto atau video, kemudian pengamatan bersama tentang mana sampiran, mana isi, dan bunyi rima di akhir kata. Setelah telinga “hangat”, barulah permainan ringan dipakai untuk mengikat pengalaman pantun, anak membaca satu baris ketika menyebut kartu, menyebut juga rimanya, dan saat berhasil menyusun bait, mereka menandai nilai etika yang mereka tangkap. Dengan cara seperti ini, membaca, mendengar, dan berbicara terjadi bersamaan tanpa tekanan yang kaku, malah menyenangkan (Anggraeni et al., 2019).
Media yang saya pilih sengaja dibuat sangat sederhana, satu dek berisi tiga belas pantun palang pintu, masing-masing dicetak empat kali sehingga totalnya 52 kartu. Tidak ada simbol daun atau hati seperti di permainan kartu remi, hanya angka 1–13 di sudut dan teks pantun yang terbaca jelas. Kesederhanaan ini memudahkan replikasi kartu dapat dicetak ulang, dibawa ke berbagai kelas, dan digunakan berulang pada pertemuan berikutnya. Yang dicari bukan “efek wah” dari media pembelajaran ini, melainkan aliran belajar yang rapi, anak bertemu bahasa berirama, melatih artikulasi, dan menyerap etika dalam suasana bermain.
Permainannya pun tak perlu banyak aturan. Setiap anak memegang tujuh kartu, sisanya diletakkan di tengah. Bergiliran, mereka menebak kartu yang dimiliki temannya, dengan syarat penebak memegang minimal satu kartu dari pantun yang sama. Saat menebak, ia membacakan satu baris dari pantun tersebut. Jika benar, kartunya berpindah, jika salah, ia menarik satu kartu dari tumpukan. Ketika satu pemain mengumpulkan empat kartu pantun yang sama, ia meletakkannya di meja, membacakan bait lengkap, dan menyebut nilai etika yang tampak di sana. Hingga bel berbunyi, pemenang bukan sekadar yang paling cepat menebak, melainkan yang paling banyak “meresmikan” bait.
Contoh Pantun I:
Ke pasar baru beli selendang,
Singgah sebentar membeli jambu.
Assalamualaikum kami datang,
Mohon izin bertamu pada Ibu/Bapak.
Contoh Pantun II:
Anyam ketupat seratnya padu,
Tersusun rapi tak mudah patah.
Terima kasih sudah bertamu,
Semoga akrab bertambah berkah.
Akhirnya, tujuan dari internalisasi budaya palang pintu ini bukan agar anak hafal nama tradisi, melainkan agar mereka mempraktikkan nilai yang dikandungnya. Ketika seorang siswa berani menyapa lebih dulu, memilih kata yang halus, dan menutup percakapan dengan terima kasih, di situlah pelajaran terasa berhasil. Palang pintu memberi teladan bahwa kata yang baik dapat membuka pintu, sekolah memberi ruang agar teladan itu menjadi kebiasaan dan kartu yang sederhana ini hanyalah jembatan yang memudahkan langkah ke arah sana bagi pemelajar.
Referensi
Melinda, A., Paramita, S., & Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. (2018). Makna Simbolik Palang Pintu Pada Pernikahan Etnis Betawi di Setu Babakan. In Koneksi (Vols. 2–2, pp. 218–225).
Wibowo, R. A., Ayundasari, L., & Universitas Negeri Malang. (2021). Tradisi Palang Pintu masyarakat Betawi dalam konteks budaya Islam. In Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Vol. 1, Issue 1, pp. 38–44) [Journal-article]. https://doi.org/10.17977/um063
Anggraeni, D., Hakam, A., Mardhiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun peradaban bangsa melalui religiusitas berbasis budaya lokal. Jurnal Studi Al-Quran/Jurnal Studi Al-Qur’an, 15(1), 95–116. https://doi.org/10.21009/jsq.015.1.05
Subarna, R., Dewayani, S., Setyowati, C. E., KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN, & PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN. (2021). Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII (By T. Harsiati & Mu’jizah; T. Hartini, Ed.; Cetakan pertama, pp. xii–220).
Fanny Gustiana. (2023). Tradisi Palang Pintu: Sejarah dan Maknanya Pada Pernikahan Adat Betawi. Diakses 8 Oktober 2025, dari https://weddingmarket.com/artikel/sejarah-palang-pintu
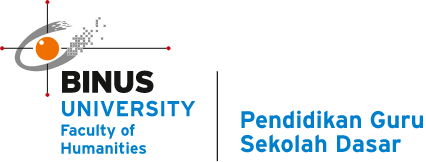




Comments :