Tradisi Sekaten sebagai Bentuk Media Internalisasi Nilai Budaya dan Pendidikan Karakter Berbasis Ethnopedagogy di Sekolah Dasar
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, di mana setiap daerah memiliki tradisi dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Kekayaan budaya ini menjadi ciri khas bangsa yang tidak hanya mencerminkan sejarah panjang, tetapi juga memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai luhur leluhur. Salah satu tradisi yang hingga kini tetap lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat adalah Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat yang berkembang di Pulau Jawa, khususnya di daerah Surakarta dan Yogyakarta, dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Upacara adat Sekaten merupakan upacara untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (Mulyana, 2017).
Sejarah upacara adat Sekaten mencerminkan proses akulturasi budaya dan penyebaran Islam di Jawa. Tradisi ini diyakini telah muncul sejak masa kerajaan Hindu–Buddha, tepatnya pada pemerintahan Prabu Brawijaya V di Majapahit pada abad ke-15 (Rahayu et al., 2020). Saat itu, sang raja mendengar kabar bahwa putranya, Raden Patah yang telah memeluk Islam berencana menyerang Majapahit bila sang prabu menolak masuk Islam. Kabar tersebut membuat Brawijaya V gelisah hingga melakukan pertapaan dua belas hari untuk memohon keselamatan rakyatnya. Melihat kesedihan rajanya, para ahli gending mencoba menghibur dengan memainkan gamelan pusaka kerajaan bernama Kanjeng Kyai Sekar Delima. Awalnya gamelan dimainkan lembut, namun kemudian diubah menjadi lebih dinamis hingga mampu membangkitkan semangat sang prabu. Sejak itu gamelan tersebut dinamai Sekati, berasal dari istilah sesek ati atau “sesak hati,” yang melambangkan perubahan duka menjadi semangat, dan menjadi cikal bakal tradisi Sekaten (Rahayu et al., 2020).
Pada masa Kerajaan Demak, tradisi ini mengalami transformasi makna. Sunan Kalijaga menjadikan Sekaten sebagai media dakwah Islam dengan menciptakan gamelan khusus untuk menarik perhatian masyarakat. Setelah warga berkumpul mendengarkan lantunan gamelan, beliau mengajarkan Islam dan menuntun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak itu gamelan Sekaten dimaknai dari kata syahadatain (dua kalimat syahadat) dan digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW (Daryanto, 2016).
Perbedaan mencolok antara Sekaten masa Majapahit dan Demak terletak pada tujuannya: jika sebelumnya berwujud selamatan bagi arwah leluhur, maka pada masa Islam menjadi sarana dakwah dan peringatan Maulid Nabi (Ahmad et al., 2021). Perjalanan tersebut menunjukkan kemampuan budaya Jawa beradaptasi dari ritual spiritual menjadi perayaan religius yang merefleksikan harmonisasi nilai Islam dan kearifan lokal. Hingga kini, tradisi ini terus dilestarikan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta melalui rangkaian prosesi Miyos Gangsa, Numplak Wajik, Kondur Gangsa, Garebeg, dan Bedhol Songsong (Ahmad et al., 2021).
- Miyos Gangsa
 Sumber: Keraton Yogyakarta. (2022).
Sumber: Keraton Yogyakarta. (2022).
Miyos Gangsa merupakan prosesi dikeluarkannya dua gamelan pusaka keraton, yaitu Kanjeng Kyai Gunturmadu dan Kanjeng Kyai Nagawilaga, dari dalam istana untuk kemudian dibawa menuju Masjid Gedhe Kauman. Sebelum diarak, kedua gamelan tersebut dibunyikan secara bergantian di Bangsal Pancaniti sejak sore hingga malam hari. Dalam prosesi ini, masyarakat memperoleh udhik-udhik campuran bunga, beras, biji-bijian, dan uang logam yang melambangkan sedekah raja kepada rakyatnya. Gamelan kemudian diarak menuju masjid dan ditabuh selama enam hari berturut-turut, kecuali pada waktu salat dan malam Jumat, sebagai simbol dakwah dan bentuk penghormatan terhadap Maulid Nabi (Ahmad et al., 2021).
- Numplak Wajik
 Sumber: Keraton Yogyakarta. (2019).
Sumber: Keraton Yogyakarta. (2019).
Prosesi berikutnya adalah Numplak Wajik, yang dilaksanakan tiga hari sebelum puncak perayaan atau pada tanggal 9 Mulud. Kegiatan ini dipimpin oleh putri tertua Sultan dan dilakukan di Panti Pareden dengan tujuan menyiapkan Gunungan Wadon yang akan digunakan dalam upacara Garebeg. Dalam waktu bersamaan, para prajurit keraton juga melakukan latihan Gladhi Prajurit untuk persiapan pengawalan upacara Garebeg (Ahmad et al., 2021).
- Kondur Gangsa
 Sumber: Keraton Yogyakarta. (2022).
Sumber: Keraton Yogyakarta. (2022).
Kondur Gangsa adalah prosesi pengembalian dua gamelan Sekaten dari Masjid Gedhe Kauman ke keraton. Prosesi ini disertai kehadiran Sri Sultan beserta keluarga dan pejabat keraton yang mengikuti upacara Maulid Nabi di masjid. Dalam prosesi tersebut, Sultan menaburkan udhik-udhik sebagai simbol kemurahan hati dan berbagi rezeki, serta menjadi bentuk penghormatan kepada masyarakat yang hadir (Ahmad et al., 2021).
- Garebeg
 Sumber: Keraton Yogyakarta. (2017).
Sumber: Keraton Yogyakarta. (2017).
Dalam prosesi ini, keraton mengeluarkan tujuh Gunungan, terdiri atas tiga Gunungan Kakung, satu Gunungan Estri, satu Gunungan Darat, satu Gunungan Gepak, dan satu Gunungan Pawuhan, yang kemudian dibagikan di tiga lokasi, yaitu Masjid Gedhe Kauman, Pura Pakualaman, dan Kepatihan. Gunungan tersebut menjadi simbol rasa syukur atas rezeki Tuhan serta wujud kebersamaan antara keraton dan rakyat (Ahmad et al., 2021).
- Bedhol Songsong
 Sumber: Keraton Yogyakarta. (2022).
Sumber: Keraton Yogyakarta. (2022).
Bedhol Songsong diadakan pada malam hari setelah Garebeg Mulud di Bangsal Pagelaran Keraton. Prosesi ini berupa pementasan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Lampahan Wisanggeni Ratu, disertai pencopotan songsong agung (payung besar kerajaan) dari plataran keraton sebagai tanda berakhirnya seluruh rangkaian upacara Sekaten (Ahmad et al., 2021).
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan Sekaten menggambarkan perpaduan antara nilai spiritual, sosial, dan seni budaya yang diwariskan turun-temurun. Setiap prosesi memiliki makna simbolik yang tidak hanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memperkuat hubungan antara kerajaan dan rakyat sebagai wujud harmoni budaya dan religiusitas masyarakat Jawa.
Tradisi upacara adat Sekaten berpotensi besar diintegrasikan ke dalam pembelajaran sekolah dasar, terutama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang menekankan pemahaman terhadap keragaman budaya dan sejarah bangsa. Setiap prosesi Sekaten seperti Miyos Gangsa, Numplak Wajik, Kondur Gangsa, Garebeg, dan Bedhol Songsong mengandung nilai religius, sosial, dan historis yang dapat dijadikan bahan ajar kontekstual. Melalui pengenalan tradisi ini, siswa tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga memetik nilai filosofis seperti gotong royong, kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur. Integrasi ini sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis kearifan lokal yang mengaitkan materi dengan kehidupan masyarakat. Melalui Sekaten, siswa belajar tentang akulturasi budaya Jawa dan Islam yang menumbuhkan toleransi, kebersamaan, serta kebanggaan terhadap identitas bangsa. Pengenalan nilai-nilai dalam tradisi ini juga memperkuat karakter religius, sosial, dan cinta budaya yang penting bagi pembentukan kepribadian.
Penerapan tradisi Sekaten dalam pendidikan bertujuan memperdalam pemahaman peserta didik terhadap nilai budaya dan ajaran Islam yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung di dalamnya mendorong kesadaran akan identitas budaya serta kebanggaan terhadap warisan leluhur (Karim & Raya, 2022). Melalui pembelajaran yang relevan dengan lingkungan budaya, integrasi tradisi ini menumbuhkan religiusitas, rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong (Novika Lestari, 2022). Dengan demikian, Sekaten tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang berkelanjutan lintas generasi. Pada akhirnya, Sekaten bukan sekadar perayaan keagamaan, melainkan simbol perpaduan seni, spiritualitas, dan nilai sosial masyarakat Jawa. Tradisi ini menjadi cerminan harmoni antara agama dan budaya, serta warisan luhur yang menuntun generasi muda menjaga kebersamaan, kepedulian, dan rasa hormat terhadap sejarah bangsanya.
Referensi
Ahmad, I., N, B. S., N, A. O., P, E. A., & P, A. R. (2021). Tradisi Upacara Sekaten di Yogyakarta Tradition of Sekaten Ceremony in Yogyakarta. 3(2), 49–53.
Daryanto, J. (2016). Gamelan Sekaten Dan Penyebaran Islam Di Jawa. Jurnal IKADBUDI, 4(10), 32–40. https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v4i10.12030
Karim, A., & Raya, M. K. F. (2022). The Acculturation Dynamics of the Sekaten Tradition in Modern Indonesia. Dialog, 45(1), 29–40. https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.510
Mulyana, A. (2017). Sekaten Tradition: The Ritual Ceremony in Yogyakarta as Acculturation Reality of Javanese Culture in Indonesia. International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), 4(2), 50. https://doi.org/10.29032/ijhsss.v4.i2.2017.50-61
Novika Lestari. (2022). The Role of Sekaten Tradition in Learning Physics to Conserve Culture in Yogyakarta. International Journal of Education and Literature, 1(1), 90–95. https://doi.org/10.55606/ijel.v2i1.62
Rahayu, N. T., Warto, Sudardi, B., & Wijaya, M. (2020). The Dynamics of Social Values and Teaching in the Global Era: The Sekaten Tradition of Surakarta Kingdom Nuryani Tri Rahayu 1 , Warto 2 , Bani Sudardi 3 & Mahendra Wijaya 4. Journal of Social Studies Education Research, 11(1), 213–229.
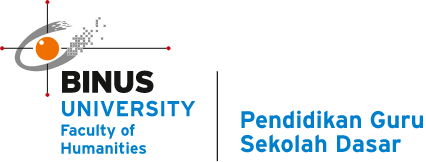



Comments :